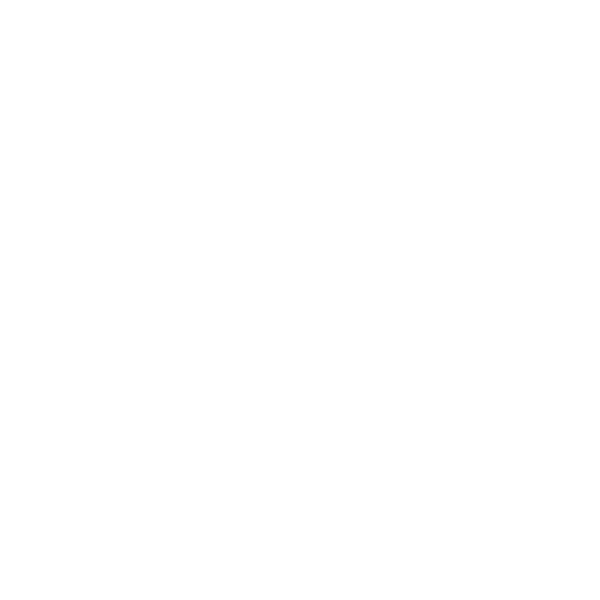Frame of reference trimatra (desa, kala, patra) sebagai sirkumstansi adaptasi acapkali (kalau tidak mau disebut seringkali) digunakan untuk memecahkan kebuntuan dalam pelaksanaan tata cara maupun kehidupan sosial kemasyarakatan agama Hindu.
Trimatra itu, bukanlah bermakna tunggal sebagai pemenuhan horizon of expectation (horizon harapan) untuk menyelesaikan dengan mudah apa yang menjadi kendala dengan sesuatu yang mudah juga. Misalnya, apabila ada kerabat yang meninggal di rumah sakit, agar tidak merepotkan diri sendiri dan keluarga simpan saja jenazahnya di cold strorage rumah sakit. Nanti, kalau sudah ada hari baik (dewasa) langsung dibawa ke setra untuk dilakukan upacara pembakaran jenazah. Mudah bukan? Apakah ini termasuk acara yang bisa dilakukan karena adagium trimatra?
Tidak mudah menjawab pertanyaan itu! Para pembela tradisi, tentu akan melontarkan kecaman atau bahkan cacian apabila hal yang seperti itu dikukuhkan sebagai kebiasaan yang dilegitimasi. Sebaliknya, bagi orang yang memandang tradisi yang sekarang ini masih berlaku sudah arkhais, sudah ketinggalan zaman, sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan keadaan masa kini sehingga adagium trimatra menjadi senjata pamungkas untuk mengesahkan penyimpangan yang dilakukan.
***
Man is animal symbolicum, begitu kata filsuf Susan Langer yang teori simbolismenya sulit dibantah. Manusia, sesungguhnya makhluk bersimbol, makhluk yang sepanjang sejarahnya senantiasa memproduksi simbol-simbol yang diperlukan. Semakin renik, semakin kompleksnya simbol yang diproduksi merefleksikan tingginya suatu kebudayaan.
Lihatlah universum simbolik dalam pemuliaan jenazah oleh pemeluk agama Hindu di Bali. Oleh para ethnograf disaksikan sebagai formulasi simbol-simbol yang kompleks sehingga disebut sebagai salah satu hasil kebudayaan yang tinggi. Betapa tidak, rangkaian pemuliaan jenazah di Bali begitu renik dan begitu kompleksnya sampai-sampai menimbulkan otokritik tidak saja sekarang ini, tetapi sudah sejak zaman dahulu kala.
Gaguritan I Ketut Bungkling yang ditulis oleh Ida Wayan Dangin dari Gria Pidada Sidemen Karangasem pada masa lalu mengungkapkan otokritik yang tajam atas budaya pemuliaan jenazah di Bali. Pada suatu hari, I Ketut Bungkling bertanya kepada seorang padanda, mengapa orang meninggal matanya ditempeli cermin? Ida Padanda menjawab dengan penuh semangat karena merasa ada orang yang mengetahui keutamaan yadnya dengan mengatakan bahwa cermin tang ditempelkan pada jenazah itu merupakan simbol bahwa kelak bila orang yang meninggal itu lahir kembali (reinkarnasi), diharapkan matanya jernih menawan. I Ketut Bungkling manggut-manggut mendengarkan dengan serius. Dengan lemah lembut kemudian ia bertanya lagi: “Kalau begitu, apakah putri Ratu Padanda pada saat meninggal dahulunya lupa ditempelkan cermin matanya sehingga lahir menjelma kembali dengan mata juling?” Tak pelak, Ida Padanda marah bukan alang kepalang mendengar pertanyaan I Ketui Bungkling demikian itu. Ida Padanda serta merta mengusir I Ketut Bungkling dengan kasar. Sembari berlalu, I Ketut Bungkling ngedumel dengan mengatakan bahwa Ida Padanda yang ditemuinya, dahulunya pastilah suka marah, tidak pantas menjadi padanda!
Demikianlah simbol yang diproduksi seperti pemuliaan jenazah dalam kebudayaan Bali yang dinilai adiluhung itu diberontaki, dipertanyakan kebenarannya, lalu ditinggalkan sedikit demi sedikit. Kalau jenazah langsung dibawa ke kuburan, maka sebagian prosesi simbolok pemuliaan jenazah itu pada dasamya sudah ditiadakan. Akan tetapi, pada siklus kehidupan selanjutnya, simbol-simbol yang diberontaki dirindukan kembali sehingga dilaksanakan kembali, digunakan lagi sebagai simbol yang ditaati.
Ada apa dengan trimatra (desa, kala, patra) dalam konteks tataran simbolik pelaksanaan ajaran agama Hindu? Makna terimplisit dari ajaran trimatra jarang diungkapkan sebagai suatu kebenaran inti dari ajaran agama Hindu.
Desa dalam adagium trimatra tidak hanya berarti tempat. Namun dapat berarti sebagai ‘wadah tempat bersemayamnya diri’. Bila secara harafiah berarti wilayah tempat tinggal orang-orang, maka pada level yang lebih tinggi, desa juga berarti tubuh ini. Anggasarira yang berbentuk inilah yang juga disebut desa.
Kalau begitu, kala yang secara harafiah berarti ‘waktu’ yang senantiasa bergerak terus sepanjang waktu apakah juga menyelipkan makna tertentu yang lebih tinggi dalam tataran religio filosofis? Sesungguhnya kata ‘kala’ mengandung lipatan makna yang renik. Mengandung berbagai macam makna yang perlu ditelusuri sesuai konteksnya. Dalam konteks trimatra agaknya kata ‘kala’ lebih merupakan ‘waktu sebagai takdir yang tidak dapat dielakkan’.
Demikian pula kata ‘patra’ yang berasal dari kata ‘patram‘ atau ‘patra’ dalam bahasa Sanskerta atau dalam bahasa Jawa Kuna menjadi ‘patrm’, mengandung pengertiaan yang kompleks sesuai konteksnya. Oleh karena, berkompleks dengan kata ‘desa’ dan ‘kata’, maka lebih dekat artinya dengan ‘daun’ sebagai ibarat yang menyatakan bahwa tubuh manusia sesungguhnya seperti daun yang pada saatnya nanti akan layu lalu menguning dan jatuh ke tanah bersatu dengan unsur yang membentuknya.
Bila demikian, maka sesungguhnya trimatra berhubungan dengan hakikat jati diri manusia yang mewujud dalam diri manusia (desa) yang terperangkap dalam waktu sebagai takdir yang tidak dapat dielakkan (kala) yang bagaikan daun (patra) yang layu pada saatnya dan akhimya menyatu dengan wujud asalinya, yaitu pertiwi, apah, teja, bayu, akasa.
Dengan pengertian yang semacam itu, dalam siklus kehidupan yang semakin hari semakin rumit karena dipengaruhi oleh yuga, maka bila menoleh bingkai desa, kala, patra sesungguhnya bukanlah berarti membenarkan tindakan permisif sebagai jalan keluar bila terdesak dengan hedonitas simpang tiga kenikmatan jasmani, kegamangan rohani, dan kebebasan dunia maya. Justru sebaliknya, melangkah di jalan dharma yang hakiki merupakan jalan “keselamatan” yang perlu dipertahankan. Kembalilah pada jati diri bahwa sesunggunya diri ini ada dalam siklus waktu yang tidak dapat dielakkan hanya untuk kembali kepada-Nya. Mokshartam Jagadhita ya ca Iti Dhama. Shanti. Shanti. Shanti.
Oleh: Jelantik Sutanegara Pidada
Source: Majalah Wartam, Edisi 31, September 2017